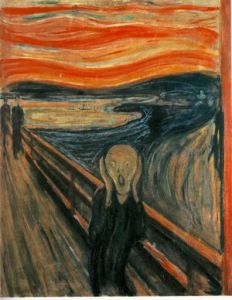Tegak lurus dengan langit, ia berdiri di puncak bukit itu. Di kepalanya bulan sabit dari langit sebelum fajar. Di kakinya Tanah kemarau, tahun ini kelewat panjang. Dalam dadanya lesu dan bingung dari dendam yang terlalu lama dipendam, dan baru saja dapat dibalaskan.
Dia baru saja membunuh seseorang. Darah masih lekat di jari-jarinya. Belati masih ia genggam. Dia lari ke bukit itu, diburu tanya: Apa selanjutnya? Setelah berkali-kali belati itu ia dorong ke jantung sang korban.
Apa selanjutnya? Ia tak tahu. Ia hanya tahu, sebentar lagi fajar akan kembang di langit. Sesudah itu, seperti 2×2 = 4, matahari bakal terbit. Belati ia lempar. Tangannya ia remas-remas. Dengan berbuat begitu, ia ingin pesiang tangannya dari gumpal-gumpal darah. Juga, ia ingin panaskan tangannya dan dengan itu tubuhnya. Dingin sebelum fajar menulang sumsum.
Dari desa di kaki bukit itu, mulai dia dengar suara-suara umat manusia yang bakal bangun. Suara dengkur di tepi lena. Suara mimpi-mimpi di babak akhirnya. Suara cumbu dan kasmaran keburu sempat. Suara di ambang hidup nyata sehari-hari.
Terpesona ia mendengarkan suara-suara tanpa definisi itu. Suara dari manusia, tanpa manusia terlihat dan berkata-kata. Suara tentang manusia. Suara yang ikut mencakup ikhwal tentang ia sendiri.
Ia telah membunuh seseorang. Siapa, apa alasannya, kurang jelas. Ia hanya tahu, dengan itu ia mungkin ingin balaskan peristiwa menghilangnya ayahnya dahulu semasa perang …. Satu hari, semasa perang, ayahnya tak pulang. Lewat seminggu, sebulan, setahun. Keluarganya memutuskan: ia hilang. Titik.
Mereka tak sadar, hilang adalah keadaan lebih parah lagi dari mati. Dari tewas. Duka oleh hilang tak boleh, tak pernah, tak pernah, penuh dan resmi. Esok lusa, si hilang bisa saja muncul kembali, segar bugar, tak kurang suatu apa. Bahkan, mungkin ia pulang bawa harta atau nama.
Tetapi, mereka sekeluarga kini sudah menunggu lebih 17 tahun. Ibunya dalam pada itu sudah meninggal pula. Pesannya, “Kalau ayahmu pulang nanti, sampaikan salam saya. Sampaikan juga, saya masih cin.”
Hampir muntah ia mendengar sentimen film India begitu dari mulut ibunya sendiri. Bah! Pikirnya, ibu kandungku sendiri sampai napas terakhirnya pecandu film India.
Ibunya dikubur. Sejak itulah mulai sejarah bencinya terhadap ayahnya, yang tak sempat ia kenal. Ia tiga tahun ketika ayahnya hilang. Ayahnya, yang dengan hilangnya itu telah menciptakan kekacauan metafisis di kalangan keluarganya.
Ia dan kedua abangnya—mereka bertiga sesaudara—selama ini tak dapat menyebut diri yatim. Ibunya tak dapat menyebut dirinya janda. Oleh sebab itu, plat nama ayahnya masih saja tak mereka turunkan dari depan rumah. Surat, koran, kuitansi, formulir penetapan pajak, semuanya masih saja mendukung nama ayahnya.
Lebih pahit lagi adalah perkumpulan dan partai ayahnya, masih saja terus melakukan tagihan-tagihan iuran tiap bulan. Apa yang dapat mereka lakukan, selain membayarnya saja? Menolak membayar berarti menyuruh mereka menjawab sejumlah tanya yang demi kesentosaan batin mereka sebaiknya jangan mereka jawab dahulu. Jangan sekarang ini! Nanti, bila semua sudah jadi sejarah— termasuk jasad mereka sendiri—pertanyaan itu boleh saja diajukan. Yang menjawabnya nanti toh sejarah juga.
Jadilah keluarga ini keluarga aneh. Mereka tiap hari bertarung melawan sejarah. Sebab, salah satu dari sekian kenyataan pahit dalam pergaulan antarmanusia adalah manusia yang satu pada dasarnya tak dapat membiarkan sendirian manusia lainnya. Didorong-dorong oleh apa yang lazim disebut sebagai kesadaran manusia modern, sosiologi, sosialisme, demokrasi, tata krama, dan entah apa lagi, tiap manusia menganggap sebagai hak, bahkan kewajiban mereka untuk ikut-ikutan mencampuri urusan manusia lain. Celakalah makhluk yang mencoba-coba menentang kecenderungan zaman ini.
Suatu hari, datang ke rumah mereka petugas sensus. “Telah sekian tahun kita merdeka, katanya. Demi gengsi kita, sebagai negara dan bangsa berdaulat—ayo! jawab, siapa, di mana, kepala keluarga ini?”
Mereka sekeluarga melongo. Hantu yang selama ini berhasil mereka bendung di luar pagar rumah dan tempurung kepala mereka, kini duduk di kursi di kamar tengah, balpoin di tangannya, formulir putih di hadapan-nya, suaranya lantang, wajahnya penuh prosa PGP.
Singkatnya: petugas sensus itu telah melenyapkan keseimbangan yang selama ini berhasil dipertahankan keluarga itu. Kedua abangnya membunuh petugas itu, mereka ditangkap, dihukum seumur hidup di tempat pembuangan yang sangat jauh.
Seorang kenalan baik, duda setengah baya, amat kaya, sering datang main bridge dan halma, menyangka dapat berbuat baik terhadap keluarga itu dengan melamar si ibu. Kebaikannya begitu besarnya, hingga hal-hal seperti peri kemanusiaan, kesadaran sosial dan kebutuhan kelamin cukup disimpulkannya dalam hanya satu gagasan saja. Yakni: menghendaki istri dari kawan baiknya yang telah menghilang.
Si ibu melongo. Rohani dan jasmaninya kacau. Rohani: bagaimana perkawinan kembali seperti ini dapat ia benarkan secara hukum, adat, moral dan agama? Dia bukan janda. Di lemarinya tak ada ia simpan surat cerai maupun surat kematian suaminya. Jasmani: bagaimana kesempatan legal seperti kawin kembali ini dapat ia lewatkan begitu saja, sedangkan ia sendiri—betul tak muda benar lagi—masih sehat, cantik? Ia tak mau jadi hanya hormon bertumpuk saja ….
Suatu pagi, anak bungsu, tokoh kita, perlu sisir. Ia masuk bilik ibunya yang ada di ranjang sedang dipeluk dan dikecup habis-habisan oleh kenalan baik yang suka sering datang main bridge dan halma itu. Mereka bertiga serempak berteriak, Tokoh kita: terperanjat sangat, tak percaya, sangat putus asa.
Ibunya seharian menangis, meraung-raung. Petangnya, ia meninggal, setelah dalam gaya film India meninggalkan pesan padanya, “Kalau ayahmu pulang nanti, sampaikan salam saya. Dan sampaikan juga, saya masih cin ….”
Tetapi di balik seluruh kekacauan ini, kerangka masalah tokoh kita ini setidaknya telah punya beberapa tonggak pasti. (1) Dia kini piatu: ini tak dapat disangsikan lagi. (2) Kedua abangnya tak bakal pernah dilihatnya seumur hidup lagi. (3) Tinggal hanya ia sebatang kara saja dari seluruh keluarganya di dunia ini. (4) PS: Ayahnya masih saja sewaktu-waktu bisa datang, pulang … mengetuk pintu, masuk, lalu membaca surat kabarnya, berbuat seolah tak ada kejadian apa-apa sama sekali selama ini.
Suatu hari, tokoh kita bertemu gadis, tunggang-langgang jatuh cinta padanya, kontan dilamarnya kawin, kontan dijawab ya, oleh si gadis.
Pesta disiapkan segera. Tetapi, sehari sebelum hari perkawinan, orang tua gadis berkeras ingin kenal orang tua mempelai laki-laki.
Kematian ibunya cepat ia ceritakan. Tetapi, kerongkongan-nya tersumbat ketika ia akan mulai tentang ayahnya. Apa yang harus dan dapat ia katakan? Ia berpendirian, perkawinan tak baik dimulai dengan bohong besar. Oleh sebab itu, ia ceritakan saja kejadian sebenarnya.
Mempelai laki-laki tak tahu, apakah ia pernah punya ayah atau tidak! Begitulah kesimpulan orang tua gadis mengenai gagasan “Ayahku hilang” itu. Mungkin ia anak gamnpang. Cinta adalah satu, tapi nama, terutama asal-usul yang baik, jelas, adalah lain, demikian kata mereka, membatalkan perkawinan, memasang advertensi di koran esoknya, minta maaf sebesarnya kepada para undangan yang sempat datang.
Bekas calon istrinya sejak itu jatuh sakit. Ia mulai batuk-batuk. Makin lama, makin kurus, makin pucat. Bulan lalu ia meninggal, di sanatorium penyakit paru-paru, juga setelah dalam gaya film India tinggalkan pesan baginya melalui juru rawat, “Sampaikan salam saya padanya. Sampaikan juga saya masih cin ….”
Sampai dengan di sini, masih dapat ia mengikuti dan memahami jalan peristiwa. Ia banyak membaca, mendengar, bahkan melihat sendiri keluarga yang terus-menerus dihantam nasib jelek, akhirnya lenyap sama sekali dari muka bumi, tak tinggalkan bekas apa-apa, kecuali kenangan keluarga-keluarga lainnya tentang mereka sebagai “keluarga malang”. Apa boleh buat! Dewa-dewa di kayangan rupanya telah memperhitungkan ia masuk ke dalam keluarga seperti itu. Takdir tak dapat dibendung. Ia telah siapkan dirinya bagi perannya dalam babak terakhir tragedi keluarganya itu.Tetapi, apa yang membuat konsentrasinya tentang drama dan tragedi keluarganya tadi tunggang-langgang, adalah kedatangan seorang laki-laki tua pagi tadi ke rumahnya. Ia ini ketuk pintu, masuk, duduk di kursi besar, baca surat kabar dan berkata dengan suara datar, “… Aku ayahmu.”
Tokoh kita melongo. Tak dapat, tak ingin ia berkata apa. Apa, mana bukti ia ini benar ayahnya? Bila benar ia ayahnya, mengapa baru sekarang ia kembali? Ke mana, di mana ia selama ini? Peristiwa apa sembunyi di belakang hilangnya ia 17 tahun yang lalu? Adakah ia ikut perang, ditawan musuh dan baru dilepas sekarang? Seandainya ia tak ikut perang, pikiran fantastis mana yang telah menyergapnya untuk pergi menghilang begitu saja dari rumahnya 17 tahun lamanya? Adakah ia jadi pedagang pasar gelap? Penyelundup senjata gelap? Atau garong? Atau, pergi bertapa ke puncak salah satu gunung berapi?
Seribu satu tanya dapat ia ajukan. Seribu satu jawab dapat ia beri. Oleh sebab itulah ia putuskan diam saja. Lagipula, siapa tahu laki-laki tua ini bukan ayahnya sama sekali. Mungkin ia ini seorang penipu. Atau seorang sinting biasa saja yang ingin bikin gara-gara, lelucon cempulang.
Akan tetapi curiganya mulai timbul ketika laki-laki tua itu berdiri, pergi ke kamar yang selama ini dianggapnya sebagai kamar ayahnya, membuka lemari yang selama ini dianggapnya sebagai lemari pakaian ayahnya, mengambil satu stel pakaian dari dalamnya. Kemudian ia pergi mandi, di kamar mandi menyanyikan lagu-lagu kesukaan ibunya almarhumah. Selesai bersalin pakaian, ia duduk lagi di kursi besar tadi.
Tokoh kita diam saja. Orang tua itu tersenyum saja— senyum lembut orang tua—sedang matanya tajam memperhatikan tokoh kita terus.
Pandangan mata inilah terutama yang membuat tokoh kita bingung. Seolah kedua bola matanya adalah bara, berpijar hitam, masuk menerobos ke dalam seluruh tubuhnya. Terlebih, ada sesuatu yang khas pada mata itu. Ia menyerupai matanya sendiri! Juga menyerupai mata abangnya yang telah membunuh petugas sensus itu. Curiganya makin besar. Ulu hatinya nyeri. Darahnya berkali-kali tersirap. Bulu kuduknya tegak. Mata! Mata itu!
Ia sebenarnya telah siap dengan pembulatan satu kesimpulan dalam dirinya bahwa laki-laki tua yang duduk di hadapannya itu, adalah seorang penipu biasa saja—ketika pandangan mata mereka tiba-tiba saling bertemu. Laksana pola listrik sejenis, elektron-elektron kedua pasang bola mata itu saling bertolakan. Tokoh kita tertunduk! Ia kalah! Kedua bola matanya lari terbirit-birit ke motif-motif permadani di bawah telapak kakinya. Mata! Mata itu!
Itulah tanda pengenal yang paling ia takuti. Sebab hanya kedua abangnya sajalah selama ini yang sanggup menentang pandangan matanya. Dan ini adalah, oleh karena mata kedua abangnya itu sama saja dengan matanya sendiri. Bulat, hitam pekat, putihnya bening, kedipnya penuh wibawa, sinar yang dipijarkannya penuh melankoli, sekaligus kekerasan, yang berbatasan dengan kekejaman.
Tak pernah ada orang lain yang sanggup menantang pandangan mata mereka. Bahkan, ibu mereka sendiri tak dapat. Adalah pandangan mata demikian, kata ibunya, yang justru membuat ia jatuh cinta pada ayahnya. Ya, mereka bertiga mewarisi mata ayahnya.
Dan kini, salah seorang ahli waris itu duduk berhadapan dengan sang pewaris….
“Ayah!”
Hanya itu. Untuk selanjutnya, ia merangkul orang tua itu. Ia benamkan kepalanya dalam pangkuannya. Ia menangis. Orang tua itu kaku saja. Tampak ia keras sekali berusaha memerangi perasaannya. Sudut-sudut mulutnya yang sudah mulai keriput itu, ia rentangkan. Bibirnya ia peras kuat-kuat menjadi satu garis tipis yang kelewat lurus. Tangannya ia genggamkan erat-erat pada tangan kursi. Ia takut, kalau tangannya itu pergi menjalar, mengelus rambut ikal bergelombang yang diempaskan ke pangkuannya itu ….
Masih saja mereka tak berkata-kata. Dalam pada itu, mereka sudah makan siang, tidur siang, mandi sore, bersaling pakaian, menghirup teh sore. Kini mereka kembali duduk di ruang tengah, berhadap-hadapan, tak berkata satu apa. Tokoh kita tunduk, sedang orang tua itu terus saja memandanginya.
Tiba-tiba saja tokoh kita memutuskan bagi dirinya sendiri, tak dapat ia lanjutkan hidupnya begini. Yakni: tunduk tepekur saja memperhatikan motif-motif permadani di ubin. Teror yang datang menyorot dari kedua bola mata orang tua itu, tak ingin ia tanggungkan lebih lama lagi.
Ia telah menanggungkan nasib dari ranting terakhir satu keluarga yang ditakdirkan bakal lenyap sama sekali dari muka bumi ini. Ia bahkan telah sedia menerima tingkahan terhadap kutuk itu dengan misalnya menerima orang tua itu misalnya mungkin ayahnya sendiri, mungkin pula tidak.
Ya, kesedihannya besar sekali. Sebab telah ia putuskan untuk tak mau membangun kerangka-kerangka persoalan yang pelik lagi bagi dirinya sendiri, yang toh tak akan banyak berhasil memberi penyelesaian apa-apa baginya. Ia letih main catur melawan dirinya sendiri. Untuk selan-jutnya ia telah pilih sebagai filsafat hidupnya: me-remis-kan dirinya dengan hidup, termasuk dengan dirinya sendiri.
Tetapi terkutuk untuk seumur hidupnya; tak bakal berani lagi ia menatap jauh-jauh ke kaki langit, tak berani melihat ke puncak-puncak gunung dan bintang-bintang di langit, hanya oleh karena ada seorang tua mempunyai sepasang mata yang sama dengan matanya sendiri, dan oleh sebab itu tak sanggup ia tantang—tidak! Ia tidak mau, tak sedia!
Secepat kilat ia temui pada motif-motif permadani di bawah telapak kakinya itu jawaban bagi seluruh persoalannya. Kalau benarlah orang tua itu ayahnya, maka adalah orang tua ini juga telah menciptakan seluruh tragedi keluarganya itu. Dengan menghilangnya abangnya membunuh petugas sensus itu. Ia pulalah sebenarnya yang telah membuat ibunya terdampar ke dalam pelukan laki-laki kenalan baik mereka yang suka datang main bridge dan halma itu, dan lempang mengantarnya ke kubur.
Terlebih lagi: kalau ia ini ayahnya, maka adalah ayahnya ini juga yang telah bikin lebih parah kekacauan dalam dirinya kini dengan justru pulangnya ia sekarang ini.
Dan seandainya orang tua ini bukan ayahnya, tetapi cuma seorang penipu atau sinting biasa saja, maka efek kedatangannya ini masih tetap sama saja: ia telah mengingatkan tokoh kita, anak bungsu dan ranting terakhir keluarga yang terkutuk bakal lenyap dari permukaan bumi ini, kepada nasib yang sedang menanti dirinya.
Bahwa dirinya sudah dapat ia anggap mulai sekarang sebagai satu pengertian yang sebenarnya tak apa-apa lagi, dan oleh sebab itu sewaktu-waktu dapat ditiadakan, baik oleh kekuatan dari luar, maupun oleh dirinya sendiri, sudah jelas baginya kini. Mengenai ini, ia tak ragu-ragu lagi dalam dirinya sebenarnya juga sudah lama tersedia satu gagasan itu—walaupun diakuinya, aktualitas itu membuatnya agak menggigil juga.
Yang harus segera diselesaikannya dalam benaknya kini adalah, tafsiran apa selanjutnya dapat ia beri kepada kedatangan orang tua itu sendiri dalam kerangka gagasannya itu. Kalau ia tak salah dalam penilaiannya, orang tua inilah sebenarnya penyebab dari seluruh duka ceritanya, lepas dari persoalan benar atau tak benar ia ayahnya yang sesungguhnya. Selanjutnya, kalau ia juga tak salah dalam penilaian berikutnya, kedatangan orang tua ini kini sebenarnya hanyalah mungkin mempunyai satu arti saja. Yaitu, sebagai motif yang dapat mempercepat pelaksanaan gagasannya tadi!
Setelah selesai motif-motif pada permadani di bawah telapak kakinya di ubin itu—lingkaran-lingkaran spiral merah, kuning, biru—diedari matanya semua, selesailah ia mengatasi gamang yang berkecamuk selama bertahun-tahun ini dalam dirinya, dan yang barusan saja beroleh klimaknya dalam menit-menit terakhir ini.
Kini ia dapat bertindak. Harus bertindak! Satu ketenangan kosmis menyelubungi dirinya. Tiap keping dari napasnya, tiap fragmen dari perasaannya, pikirannya, pengideraannya, mulai kini adalah bagian dari satu perhitungan yang sangat teliti.
Ia pergi ke dapur. Diambilnya sebilah belati. Dia kembali. Tenang ia tantang pandangan mata orang tua itu. Orang tua itu tersenyum. Kemudian, tenang sekali, ia tikamkan belati itu ke dalam dada orang tua itu. Berkali-kali.
Orang tua itu rebah. Darahnya menutupi lingkaran-lingkaran spiral, merah, kuning, biru di permadani. Lama tokoh kita tegak memandangi mata mayat terbelalak itu. Seluruh peralihan sinarnya, dari bening hingga redup seperti susu keruh itu, disaksikannya. Akhirnya pelupuk mata redup itu dikatup-kannya. Tertutup! Tertutup sudah danau keruh itu!
Apa selanjutnya? Ia tak tahu. Tiba-tiba ia merasa dirinya seperti srigala hutan yang bingung, sebab danau tempat ia biasa minum, baru saja tertimbun tanah longsor. Ia menjalar sedahsyatnya. Seluruh isi hutan diam menggigil ketakutan. Kemudian ia lari.
Kenapa? Tak peduli. Pokoknya: lari. Kencang!
Pelan-pelan pada selimut langit terkuak warna putih abu-abu. Ke bumi memantul bayang mainan warna di langit ini. Bulan sabit miring ke tenggara. Angin daratan bertolak ke pantai. Kelelawar-kelelawar berpulangan ke pohonnya.
Sekali lagi ia remas-remas tangannya. Gumpal darah penghabisan ia jentikkan dari kuku kelingking kirinya. Ia tarik napas panjang.
Gagasannya kini telah selesai ia laksanakan. Ia puas. Nanti, setelah matahari terbit, ia akan pulang ke rumah, mandi, bersalin pakaian, sarapan pagi. Sesudah itu ia akan pergi ke kantor polisi.
Apabila ayam pertama berkokok nanti, senyum lebar kembang di wajahnya. Senyum yang sangat membebaskan. Tegaknya ia hadapkan pada matahari bakal terbit, tegak lurus dengan langit.
Iwan Simatupang
Penerbit Sinar Harapan, 1982